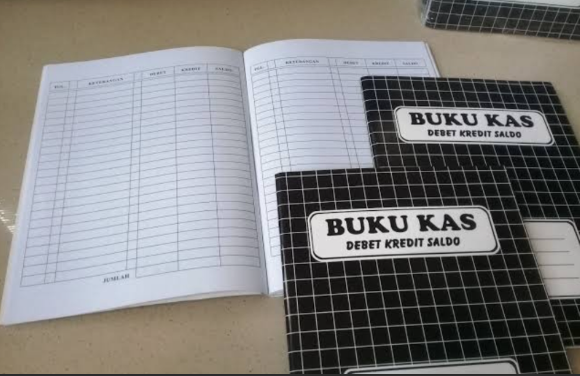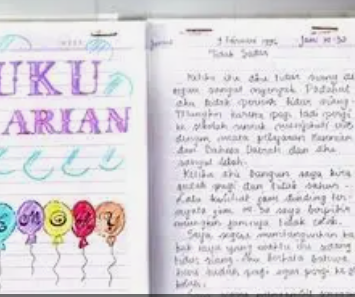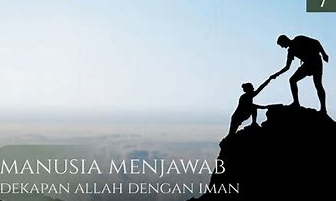GENERASI KINI, DI ERA POST-TRUTH
Kegiatan
pendidikan formal terus menjadi prioritas dalam banyak keluarga, diiringi
dengan keberlangsungan ritual yang tak henti digelar, mulai dari pesta
pernikahan hingga seremoni adat termasuk kematian. Di balik dinamika tersebut,
lahan-lahan warisan terus dilepaskan, satu demi satu berpindah tangan.
Penjualan tanah bukan lahir dari kemalasan, melainkan dari desakan hidup yang
kian tak proporsional: biaya pendidikan yang melambung, tuntutan sosial dalam
pelaksanaan pesta adat, serta beban kolektif dalam momen-momen berkabung dan
perayaan keluarga. Warisan tanah yang dahulu menjadi simbol ketahanan ekonomi
dan kedaulatan keluarga, kini berubah menjadi sumber likuidasi cepat demi
memenuhi kewajiban yang dianggap mendesak dan bermartabat secara sosial.
Ironisnya,
pembiayaan pendidikan melalui penjualan aset tanah tidak selalu berbanding
lurus dengan terbangunnya etos perjuangan. Gaya hidup konsumtif justru lebih
menonjol ketimbang orientasi intelektual atau sosial-transformasional.
Prioritas beralih dari pengembangan kapasitas diri menuju pemeliharaan citra
sosial. Realitas ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi nilai, dari
semangat belajar demi perubahan, menuju pembentukan identitas semu yang dirawat
melalui tampilan luar. Dalam konteks ini, pengorbanan generasi sebelumnya tidak
diterjemahkan sebagai warisan tanggung jawab, melainkan dimaknai secara sempit
sebagai peluang menikmati fasilitas, tanpa refleksi mendalam tentang ongkos
sosial dan emosional yang telah dibayar.
Penjualan
tanah seringkali tidak lagi mencukupi untuk menjawab kompleksitas kebutuhan
ekonomi rumah tangga modern. Dalam kondisi semacam itu, akses terhadap pinjaman
mikro berbunga tinggi menjadi solusi semu yang dengan cepat diambil. Koperasi
harian dan mingguan, yang dalam konsep awalnya dimaksudkan untuk mendukung
solidaritas ekonomi komunitas, berubah menjadi instrumen pemiskinan struktural.
Skema peminjaman yang tampak ringan di awal justru menyimpan jebakan bunga
majemuk yang tak transparan. Uang sejumlah lima ratus ribu rupiah, misalnya,
kerap menuntut pengembalian hingga delapan ratus ribu rupiah dalam hitungan
minggu, tanpa ruang negosiasi dan tanpa perhitungan risiko yang adil. Praktik
gali lubang tutup lubang pun menjadi keniscayaan. Satu pinjaman digunakan untuk
menutup pinjaman sebelumnya, menciptakan lingkaran setan ekonomi rumah tangga
yang hanya berputar pada pembayaran bunga dan denda. Produktivitas kerja tidak
lagi diarahkan untuk membangun masa depan atau mendukung pendidikan anak,
melainkan diarahkan sepenuhnya untuk menyelamatkan cicilan jangka pendek yang
terus menumpuk. Energi, waktu, dan martabat keluarga akhirnya tersedot habis
oleh sistem ekonomi yang mengandalkan tekanan psikologis dan rasa malu sebagai
alat kontrol sosial. Dalam situasi ini, bukan hanya kekayaan yang tergerus,
tetapi juga daya hidup, semangat berinisiatif, dan kepercayaan antaranggota
komunitas.
Fenomena
ini mencerminkan wajah rapuh masyarakat kontemporer di era post-truth, sebuah
masa ketika fakta dikaburkan oleh emosi, dan nilai dikalahkan oleh pencitraan.
Rasionalitas moral tergantikan oleh pertimbangan impresi, keputusan diambil
bukan berdasarkan substansi, tetapi berdasarkan respons publik yang dibangun
secara artifisial. Dalam lanskap semacam itu, keyakinan tradisional bahwa
pendidikan anak merupakan jalan utama menuju perubahan sosial masih bertahan
kuat. Namun, keyakinan tersebut tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai
terhadap perubahan struktural dalam sistem pendidikan dan ekonomi modern.
Saat
ini, dukungan pendidikan dalam bentuk beasiswa, bantuan pemerintah, dan skema
keringanan biaya sebenarnya tersedia dalam jumlah signifikan. Institusi negara
dan lembaga donor telah menyediakan jalur alternatif yang meringankan beban
pembiayaan pendidikan tinggi. Namun kenyataan menunjukkan, pengorbanan keluarga
tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, tekanan sosial dan tuntutan gaya hidup
justru memperbesar beban secara kultural dan psikologis. Paradoks ini
memperlihatkan bahwa yang sedang berlangsung bukan hanya pertarungan antara
kemiskinan dan pendidikan, tetapi juga konflik antara nilai dan persepsi, antara
martabat yang seharusnya dirawat, dan gengsi yang terus dikejar. Dalam realitas
seperti ini, pengorbanan bukan lagi diarahkan untuk menciptakan masa depan yang
lebih bermakna, melainkan untuk menjaga ilusi keberhasilan yang tampak dari
luar.
Masalah
mendasarnya terletak bukan pada akses terhadap fasilitas, melainkan pada cara
pandang terhadap hidup dan tanggung jawab. Ketika simbol kemajuan dibatasi pada
benda genggam, gaya hidup urban, dan kebanggaan akademik yang lepas dari akar,
maka yang lahir adalah generasi yang tercerabut dari realitas konkret. Relasi
dengan tanah, alam, dan tradisi berubah menjadi cerita yang asing; keterampilan
dasar seperti bertani, memasak sendiri, atau menghormati ritus kampung perlahan
terkikis oleh ambisi digital dan euforia kota.
Ketimpangan
antara simbol dan substansi kian melebar. Di satu sisi, gelar akademik
dikibarkan sebagai pencapaian, di sisi lain, harga yang dibayar oleh keluarga, dalam
bentuk lahan terjual, warisan budaya yang dilupakan, dan hubungan antargenerasi
yang renggang, tidak dianggap sebagai bagian dari narasi kesuksesan. Inilah
ironi kontemporer: pendidikan berhasil membawa tubuh ke kota, tetapi gagal
mengakarkan jiwa pada tanah asal. Dalam situasi semacam ini, beasiswa bukan
lagi alat pemberdayaan, melainkan bisa menjelma menjadi instrumen pemutusan
dari identitas kolektif.
Kesunyian
para orang tua bukan pertanda restu, melainkan bentuk paling lirih dari
penderitaan. Tatapan mereka yang kosong di beranda rumah adalah puisi luka yang
tak terbaca oleh algoritma media sosial. Dalam budaya yang dulu menjunjung
tinggi ungkapan “anak adalah kehormatan keluarga,” kini anak berubah menjadi
investasi yang belum tentu kembali. Relasi kekeluargaan yang dulunya dibangun
di atas rasa hormat dan keterhubungan emosional kini digantikan oleh transaksi
singkat, kiriman pulsa, komentar singkat di WhatsApp, atau video call sekali
sebulan. Padahal, yang dirindukan bukanlah pemberian, melainkan kehadiran.
Bukan transfer uang, melainkan tatap muka yang tulus dan hangat.
Di
tengah perayaan digital dan gemerlap identitas online, luka-luka batin di
kampung terus bertambah. Rumah-rumah tua berdiri sepi, ladang-ladang
ditinggalkan, dan para orang tua menua dalam diam yang panjang. Sementara itu,
dunia virtual sibuk menampilkan keberhasilan palsu yang dirayakan dengan emoji,
tetapi kosong dari empati sejati. Inilah krisis yang nyata, krisis kasih yang
tak bersuara namun merobek nurani. Sebab kasih sejati bukan ditunjukkan lewat
unggahan, tetapi lewat pulang yang sungguh, lewat pelukan yang benar, dan lewat
keberanian untuk mengingat dari mana hidup pernah dimulai. Jika keadaan ini
terus dibiarkan, keberhasilan akademik akan menjadi kulit kosong yang rapuh, indah
dilihat, tapi hampa makna. Ketika generasi muda tak lagi tahu cerita di balik
sebongkah nasi atau sepotong kayu rumah, maka yang hilang bukan sekadar
pengetahuan praktis, tetapi kepekaan eksistensial. Masyarakat akan tumbuh
menjadi koloni urban tanpa ingatan, berjalan cepat tanpa arah, cerdas secara
teknis namun miskin secara batin. Inilah risiko paling mengkhawatirkan:
modernisasi tanpa pendalaman, mobilitas sosial tanpa moralitas sosial.
Tanpa
kesadaran akan asal-usul, pendidikan justru bisa menjauhkan manusia dari
kemanusiaannya sendiri. Bukannya menjadi sarana pemberdayaan, pendidikan
berubah menjadi panggung individualisme yang menumpulkan kepedulian. Sebab, apa
gunanya meraih gelar tinggi jika itu membuat seseorang lupa cara menyapa
tetangga, lupa bagaimana cara duduk bersila di tanah, lupa rasanya mencium
tangan orang tua dengan sepenuh hormat? Ketika akar budaya dicabut demi citra
modern, maka lahirlah manusia yang tercerabut dari tanahnya dan tersesat dalam
bayang-bayangnya sendiri. Sudah saatnya warisan dipahami bukan sebagai
peninggalan benda, tetapi sebagai panggilan jiwa. Tanah leluhur bukan sekadar
bidang ukur dalam sertifikat; tanah adalah kitab kehidupan yang mencatat peluh,
doa, dan air mata generasi terdahulu. Menjualnya demi gengsi berarti mencabut
akar identitas dan menukar kesetiaan dengan kesementaraan. Setiap transaksi
yang mengorbankan tanah warisan untuk gaya hidup sesaat merupakan bentuk
amnesia kolektif, lupa bahwa tanah itu saksi kesetiaan dan ketekunan yang
membesarkan peradaban keluarga.
Bangkit
berarti melawan arus konsumtif yang meninabobokan kesadaran. Bangkit berarti
menolak hidup sekadar sebagai pengguna, dan memilih menjadi penjaga. Bangkit
berarti berani hidup sederhana demi martabat, bukan bermewah-mewah demi
pengakuan palsu. Tanpa kesadaran ini, generasi berikut hanya akan berdiri di
atas puing, bukan di atas fondasi kokoh yang diwariskan oleh keteguhan para
pendahulu. Kini, arah sejarah ditentukan oleh keputusan generasi muda, menjadi
penerus nilai atau pelupa jejak. Sejarah tidak bersifat netral. Jejak yang
dijaga akan melahirkan harapan, sedangkan nilai yang dijual akan meninggalkan
kehampaan. Maka, satu hal menjadi terang: masa depan tidak dibeli dengan
gengsi, melainkan dibangun dengan kesetiaan. (KU)
Tag
Berita Terkait

LEBENSWELT TABUA: KOSMOLOGI KEBERSAMAAN ATONI PAH METO DALAM CERMIN FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

Tag
Arsip
Kue Pelangi Menakjubkan Terbaik
Final Piala Dunia 2022
Berita Populer & Terbaru
Jajak Pendapat Online