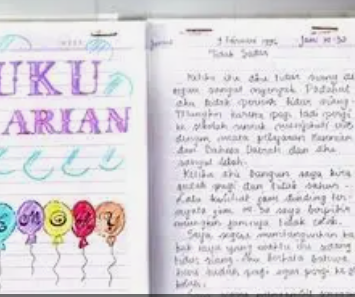Sore kemarin, langit kampung Oelbonak seolah menunduk. Awan-awan kelabu berarak pelan, seakan ikut menyimpan pilu yang berat untuk diungkapkan. Tidak ada yang berani tersenyum, tidak ada sapaan riang di halaman rumah sederhana itu. Yang ada hanyalah wajah-wajah muram: keluarga yang kehilangan putri tercinta, sahabat yang kehilangan teman seperjuangan, dosen yang kehilangan murid yang pernah mereka bimbing, serta rekan seangkatan yang masih sulit menerima kenyataan bahwa salah satu dari mereka sudah berpulang sebelum sempat mengecap manisnya panggung wisuda.
Momen Penyerahan Ijazah
Di tengah suasana itu, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Keuskupan Atambua, Rm. Theodorus Asa Siri, hadir dengan langkah perlahan. Tangannya menggenggam dua benda yang sangat berarti, sebuah Alkitab dan selembar ijazah. Selain itu, beliau juga, menyampaikan ucapan turut berduka dari Uskup Tanjung Selor, Mgr. Paul Ola. Dengan suara yang nyaris tertahan oleh haru, beliau menyerahkan Alkitab itu terlebih dahulu untuk disimpan di dalam peti jenazah, diletakkan dekat kepala Celsi. Sebuah tanda bahwa firman Tuhan akan selalu menyertai perjalanan terakhirnya, seolah menjadi pelita yang menerangi jalan pulangnya ke rumah Bapa.
Setelah itu, tibalah saat paling memilukan. Sang Ketua dengan penuh hormat menyerahkan sebuah map biru berisi ijazah, buah dari perjuangan panjang Celsi, ke tangan bapak dan mamanya Celsi. Suasana yang semula hening mendadak pecah oleh tangis. Sang ibu memeluk map biru itu erat-erat, seakan ingin memeluk tubuh anaknya yang kini hanya terbujur diam dalam peti. Jemarinya gemetar, matanya sembab, dan isaknya merobek keheningan sore itu. "Akan saya apakah ijazah ini? Mama mau buat apa dengan ijazahmu? Celsiiiiii," kata sang bunda dengan isak tangis. Sang ayah hanya bisa menunduk. Bibirnya rapat, tak ada kata yang terucap, namun air matanya jatuh deras, menjadi saksi betapa beratnya melepaskan putri yang baru saja meraih garis akhir studinya.
Di situ, semua orang sadar, ijazah yang biasanya menjadi tanda kebanggaan dan kemenangan, kini berubah wujud menjadi simbol perpisahan. Gelar yang mestinya disambut dengan tepuk tangan dan sorak gembira di aula wisuda, justru diterima dalam suasana duka yang mencekam. Sebuah kemenangan akademik yang tidak pernah sempat Celsi terima sendiri, melainkan hadir sebagai warisan abadi untuk kedua orangtuanya yang kini memeluknya dengan hati yang hancur.
Gaudeamus di Tengah Isak
Menjelang peti jenazah diusung, sebuah momen yang tak biasa terjadi. Rm. Sixtus Bere, sang pastor rekan Paroki Haumeni berdiri, suaranya lembut namun tegas, mengundang kawan-kawan seangkatan Celsi untuk maju. Dengan air mata yang belum kering, mereka berdiri di pelataran rumah, lalu bersama-sama melantunkan lagu Gaudeamus Igitur. Lagu yang biasanya dinyanyikan penuh semangat di aula wisuda, kini terdengar lirih, patah-patah, namun sarat makna. Lagu Gaudeamus Igitur, lagu tradisional mahasiswa Eropa, sering disebut juga De brevitate vitae , tentang singkatnya hidup.
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem, Nos habebit humus. Artinya, Marilah kita bergembira, selagi kita masih muda. Sesudah masa muda yang menyenangkan, sesudah masa tua yang penuh penderitaan, bumi akan memiliki kita (pada akhirnya tanah akan menelan kita).
Namun di halaman rumah duka itu, bait klasik yang kerap dinyanyikan dalam seremoni kelulusan tidak lagi terdengar sebagai seruan keriangan, melainkan sebagai ratapan penuh kasih. Nyanyian yang semestinya mengiringi puncak kemenangan akademik, justru menjadi kidung perpisahan yang meluruhkan hati.
Setiap kata yang terucap berubah fungsi, dari ajakan untuk merayakan hidup, menjadi doa untuk mengantar jiwa sahabat mereka menuju kehidupan kekal. Tangisan pecah di sela-sela nyanyian, namun mereka tetap bernyanyi, seolah ingin meneguhkan bahwa perjalanan Celsi di dunia ini telah selesai, tetapi kemenangannya tetap abadi.
Di tengah isak itu, Gaudeamus Igitur menjelma bukan lagi sebagai lagu mahasiswa semata, melainkan sebagai litani perpisahan. Lagu itu seakan berkata, kegembiraan sejati tidak berhenti pada usia muda atau tua, melainkan berlanjut di hadapan Allah. Dan itulah keyakinan yang mereka hadiahkan kepada Celsi, bahwa ia kini sedang merayakan gaudeamus yang sesungguhnya, di rumah Bapa.
Nama yang Abadi
Tak berhenti di situ. Sebelum nyanyian Gaudeamus dimulai, suasana rumah duka hening ketika Ayu Kehi, salah satu sahabat dekat, yang dulu bersama Celsi melaksanakan Magang III di Tanjung Selor, tanah Borneo, melangkah maju. Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan, ia membacakan puisi berjudul CELSI, NAMA INI. Kata-kata dalam puisi itu seakan menggema lebih kuat daripada ratapan: sebuah kesaksian bahwa setiap nama yang diukir dengan kasih dan perjuangan takkan pernah pudar, bahkan oleh maut.
Saat Ayu menyebut kata demi kata, bait demi bait, banyak yang menunduk, tak sanggup menahan air mata. Kesan hidup yang berbicara, meninggalkan pesan terakhir tentang arti hidup, perjuangan, dan keabadian cinta. Puisi itu menjelma warisan jiwa, menjembatani dunia yang fana dengan dunia yang kekal.
Langkah Terakhir Menuju Peristirahatan
Tak lama, prosesi pengantaran jenazah dimulai. Perlahan, peti yang memeluk tubuh Celsi diusung menuju pemakaman kampung. Setiap langkah diiringi doa-doa lirih, kidung yang bergetar, dan rintihan batin yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Di sepanjang jalan, hanya terdengar suara tangis yang bercampur dengan doa, seakan seluruh alam ikut mengantar gadis yang sederhana namun penuh warna itu menuju peristirahatan terakhirnya.
Tiba di pemakaman, doa kembali dinaikkan, berkat makan pun dilaksanakan sesuai tradisi. Semua berlangsung dengan hikmat, dalam keheningan yang nyaris membekukan waktu. Di sanalah, kesedihan yang mendalam berpadu dengan iman yang teguh. Kesedihan karena kehilangan sosok yang mereka cintai, iman karena percaya bahwa kini Celsi tidak lagi menanggung sakit, melainkan sudah duduk di meja perjamuan abadi bersama Tuhan.
Ketika tanah terakhir ditabur di atas pusara, banyak yang masih enggan beranjak. Sahabat-sahabat seangkatannya berdiri kaku, dan keluarga hanya bisa berpegangan satu sama lain untuk menahan gelombang duka. Lilin dinyalakan di atas pusara sang putri, di tengah suasana sore jelang gelap. Para sahabat masih berada di sekitar pusara. Dan akhirnya, semuanya pulang dengan langkah berat, membawa pulang kenangan yang terus meneteskan air mata.
Namun, di balik semua kesedihan itu, ada keyakinan yang perlahan tumbuh, perjuangan Celsi tidak pernah sia-sia, tidak pernah terhenti hanya karena ia berpulang. Ia tetap hidup dalam ingatan setiap orang yang mengenalnya, dalam doa-doa yang terucap setiap kali namanya disebut, dan dalam gelar akademik yang kini tidak hanya tertulis di atas ijazah, tetapi juga terpatri di hati semua yang mencintainya.
Celsi mungkin sudah tidak bersama mereka secara ragawi, tetapi cahaya dan semangatnya menjelma dalam setiap cerita, dalam setiap tawa yang pernah ia tinggalkan, dan dalam setiap pelukan doa yang selalu mereka panjatkan. Ijazah itu memang menjadi yang terakhir, tetapi bukan akhir dari kisahnya. Kisah Celsi akan terus hidup, karena cinta tidak pernah mati. (KU)
Tag
Berita Terkait

LEBENSWELT TABUA: KOSMOLOGI KEBERSAMAAN ATONI PAH METO DALAM CERMIN FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

Tag
Arsip
Kue Pelangi Menakjubkan Terbaik
Final Piala Dunia 2022
Berita Populer & Terbaru
Jajak Pendapat Online