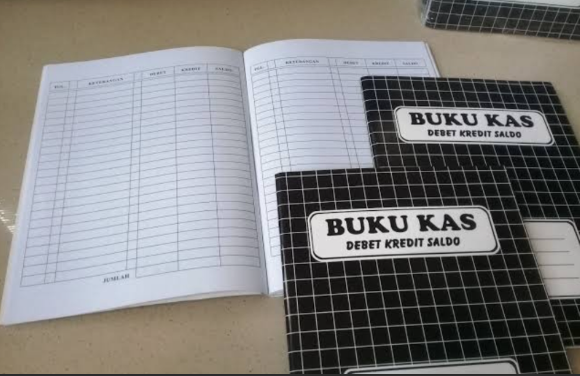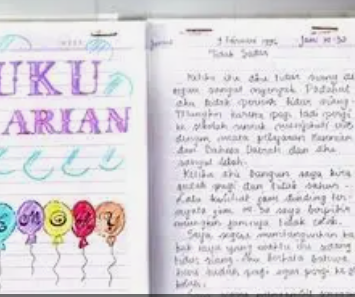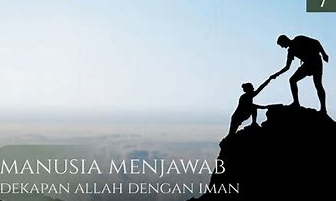Di
tanah Timor yang kering, berbatu, dan penuh cerita, tanah tempat suku Atoni Pah
Meto berakar, umat Paroki Santo Yohanes Pemandi Naesleu menyalakan devosi
mereka kepada Bunda Maria dengan cara yang begitu hangat dan khas. Sepanjang
bulan Rosario, arca Bunda Maria berkeliling dari satu lingkungan ke lingkungan
lain, bukan sekadar sebagai tradisi, tetapi sebagai perjumpaan rohani yang
hidup. Sejak arca Bunda Maria keluar dari Gereja Naesleu, hingga masuk kembali
di akhir bulan Oktober 2025, di setiap lingkungan, selalu disambut dengan doa
dan nyanyian yang lembut serta tarian, lalu diselimuti dengan kain tenun Atoni
Pah Meto, hasil karya tangan perempuan yang penuh doa dan makna. Setiap helai
benang yang melingkari arca kudus ini, seolah mengisahkan cinta dan iman yang
telah ditenun dari generasi ke generasi.
Dalam kekayaan simbolik itu, umat Naesleu memanggilnya dengan gelar yang sarat rasa hormat dan kasih: Bife Amasat Pah Meto, Perempuan Cantik dari Tanah Kering. Sebuah nama yang bukan hanya menggambarkan keelokan rupa, tetapi menyingkap keindahan batin, kelembutan hati, dan keteguhan iman Maria di tengah realitas tanah yang keras. Di balik gelar itu, umat melihat cermin dirinya sendiri: kesetiaan yang tetap menyala meski didera panas dan debu kehidupan, dan kasih yang terus berakar di tanah yang tampak tandus, namun penuh rahmat.
1. Bife Amasat: Keindahan yang
Menyala dari Hati
Dalam
bahasa Atoni, bife berarti perempuan, sedangkan amasat berarti
cantik. Namun kecantikan yang dimaksud bukanlah pesona wajah atau rupa
lahiriah, melainkan keindahan batin yang memancar dari kesetiaan, kelembutan,
dan kekuatan hati. Itulah sebabnya umat Naesleu menyebut Maria sebagai Bife
Amasat, perempuan yang cantik karena hatinya penuh iman, yang tetap
bersinar di tengah panas dan debu kehidupan sehari-hari.
Kecantikan
Maria ini selaras dengan kesaksian Kitab Suci, “Engkau sungguh cantik,
kekasihku, tiada cela padamu” (Kid 4:7). Ayat ini, dalam tradisi Gereja, sering
ditafsirkan sebagai gambaran kemurnian dan keanggunan rohani Maria. Para Bapa
Gereja, terutama Santo Ambrosius, memandang Maria sebagai citra Gereja sendiri,
murni dalam tubuh dan roh, serta menjadi teladan ketaatan dan kasih yang
sempurna (Ambrosius, De Virginibus; Kidung Agung 4:7; documentacatholicaomnia.eu).
Karena
itu, ketika umat Naesleu memanggilnya Bife Amasat, mereka tidak sedang
menghias nama Maria dengan pujian, tetapi menyatakan pengalaman iman yang dalam,
Maria adalah wajah keindahan yang menguatkan jiwa di tanah yang keras dan
kering; pancaran kasih Allah yang memperindah hidup dan meneguhkan harapan di
tengah kekeringan dunia.
2. Pah Meto: Tanah Kering yang
Mendalam Maknanya
Dalam
bahasa Atoni, pah berarti tanah atau wilayah, sedangkan meto
berarti kering. Namun bagi masyarakat Atoni, Pah Meto bukan sekadar
deskripsi geografis tentang tanah tandus di bawah terik matahari. Pah Meto adalah
simbol kehidupan itu sendiri. Tanah kering dipandang sebagai aina atau ena
(tergantung dialek wilayah), ibu yang menopang, memberkati, dan menumbuhkan
eksistensi manusia. Dari tanah ini manusia berasal, dan kepadanya pula manusia
kembali. Maka, tanah kering bagi komunitas Atoni bukan hanya tempat berpijak,
melainkan ruang relasi spiritual yang menyatukan manusia, leluhur, dan Sang
Pencipta dalam kesatuan kosmis yang sacral.
Pandangan
dunia Atoni (world-view) selalu menempatkan manusia sebagai bagian dari
jalinan relasional yang utuh. Alam, leluhur, dan Tuhan tidak berdiri terpisah,
tetapi saling menjiwai dan menghidupi. Ritual-ritual seperti Poitan Liana
menjadi ungkapan konkret dari kesadaran ini, bahwa hidup manusia berakar pada
hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan tanah serta leluhur yang
mendahului mereka.
Ketika
umat Naesleu menyambut arca Bunda Maria dengan menyelimutinya menggunakan selendang,
tais dan kain tenun khas Atoni, tindakan itu bukan sekadar ungkapan estetika
atau penghormatan simbolik. Dalam tindakan itu, mereka sesungguhnya sedang
menenun kembali ikatan antara langit dan bumi, antara dunia ilahi dan dunia
manusia. Dalam pelukan kain tenun itu, Maria dihadirkan sebagai Aina atau
Ena Pah Pinan, ibu tanah yang merengkuh anak-anaknya dengan kasih,
sekaligus jembatan antara dunia roh dan dunia nyata.
Ajaran
sosial Gereja memberikan landasan teologis bagi pemaknaan ini. Paus Fransiskus
dalam Laudato Si’ No. 241 menegaskan bahwa Maria memiliki tempat yang
istimewa dalam relasi antara manusia dan ciptaan; melalui peran keibuannya, ia
turut merasakan penderitaan alam dan memeluk seluruh ciptaan dengan kelembutan
kasih yang menebus. Dengan demikian, gelar Bife Amasat Pah Meto bukan
hanya penghormatan budaya, melainkan pengakuan iman, Maria hadir sebagai
penjaga bumi yang gersang, penenun kasih yang memulihkan relasi antara manusia
dan tanah, antara ciptaan dan Sang Pencipta.
3. Tenun sebagai Ekspresi Teologi
Inkarnasi
Dalam
budaya Atoni Pah Meto, menenun bukanlah sekadar keterampilan tangan atau
kegiatan ekonomi. Menenun merupakan tindakan yang sarat makna spiritual dan
sosial. Setiap helai benang yang disilangkan memuat kisah identitas, sejarah
keluarga, serta ingatan kolektif komunitas. Motif-motif seperti buna, kait,
adalah simbol visual dari kebijaksanaan lokal yang diwariskan antar
generasi. Menenun adalah pekerjaan suci para perempuan Atoni Pah Meto, tindakan
penciptaan yang menghubungkan dunia yang kasatmata dan yang ilahi.
Ketika
kain tenun disampirkan pada arca Bunda Maria, umat Naesleu sesungguhnya sedang
melukiskan sebuah pernyataan iman yang mendalam, bahwa Allah sendiri telah
“menenun keselamatan” di dalam rahim seorang perempuan. Gambaran ini selaras
dengan ungkapan Mazmur, “Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku” (Mzm
139:13), yang menegaskan bahwa kehidupan manusia lahir dari benang-benang kasih
dan karya tangan Allah. Dengan demikian, tindakan menghiasi arca Maria dengan
tenun lokal menjadi simbol bahwa karya keselamatan Ilahi telah dijalin di
tengah budaya dan tanah mereka sendiri.
Dalam
terang teologi Kristiani, misteri Inkarnasi dapat dimengerti sebagai “penenunan
kasih Allah” ke dalam sejarah manusia melalui rahim Maria. Allah yang tak
terbatas rela mengambil bentuk manusia, merajut kodrat ilahi dengan kodrat
manusia dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Santo Agustinus dalam Sermo 169.11
menegaskan hal ini secara mendalam, “Qui creavit te sine te, non iustificat
te sine te” artinya Dia yang menciptakan engkau tanpa engkau, tidak akan
menyelamatkan engkau tanpa engkau.” Dalam ungkapan ini, partisipasi manusia,
terutama Maria, menjadi jantung dari misteri keselamatan.
Dengan
demikian, kain tenun yang melilit arca Maria bukan sekadar perhiasan budaya,
tetapi ikon teologis, tanda bahwa karya penyelamatan Allah tidak terjadi di
luar manusia dan kebudayaannya, melainkan menjelma di dalamnya. Setiap helai
benang menjadi metafora dari Inkarnasi itu sendiri, kasih Allah yang dijalin
dalam sejarah manusia, dalam tubuh seorang perempuan, dan kini, dalam warisan
budaya Atoni Pah Meto.
4. Religiusitas Atoni Pah Meto dan
Inkulturasi Gerejawi
Religiusitas
Atoni Pah Meto menampakkan wajah iman yang sangat konkret, relasional, dan
komunikatif. Iman bukanlah seperangkat konsep abstrak, melainkan pengalaman
yang diungkapkan melalui ritus, simbol, dan tindakan bersama. Dalam setiap
ritual agraris, mulai dari doa untuk hujan hingga syukur atas panen, terkandung
makna sosial, ekologis, dan religius yang memperkuat rasa kebersamaan dan
menjaga harmoni antara manusia, alam, dan yang ilahi. Melalui ritus-ritus
semacam ini, komunikasi simbolik terjalin, manusia tidak hanya berbicara kepada
Tuhan, tetapi juga kepada tanah, leluhur, dan sesama dalam sebuah dialog kosmis
yang menyatukan.
Dalam
pandangan dunia Atoni, kehidupan manusia selalu dilihat dalam jalinan yang utuh
antara Tuhan (Uis Neno), alam, dan komunitas. Segala sesuatu hidup dalam
relasi dan saling ketergantungan, tidak ada batas tegas antara sakral dan
profan. Karena itu, ketika umat Naesleu menghiasi arca Bunda Maria dengan kain
tenun Atoni Pah Meto, tindakan itu bukanlah bentuk sinkretisme atau pencampuran
iman yang dangkal, melainkan perwujudan inkulturasi yang sejati. Gereja tidak
datang untuk menghapus simbol-simbol lokal, tetapi untuk menanamkan Injil di
dalamnya, agar Sabda Allah berakar dalam tanah dan budaya umat.
Semangat
inkulturasi ini sangat sejalan dengan ajaran Konsili Vatikan II. Dalam Gaudium
et Spes No. 53, para Bapa Konsili menegaskan bahwa budaya manusia adalah
wadah tempat iman berakar dan bertumbuh, serta Gereja dipanggil untuk
menghormati, memurnikan, dan mengangkat nilai-nilai lokal sebagai sarana
pewartaan Injil. Dengan demikian, tindakan umat yang memadukan simbol budaya dalam
devosi kepada Maria adalah wujud nyata dari Gereja yang bertumbuh di tanahnya
sendiri, Gereja yang mengenakan wajah lokal tanpa kehilangan jantung
universalnya.
Paus
Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Mater No. 46 menegaskan bahwa Maria
adalah ikon Gereja dalam peziarahan iman, figur yang mengajar umat untuk
membuka diri kepada karya Roh Kudus di tengah sejarah dan kebudayaannya. Ketika
dedikasi mariani diinkulturasi dalam bentuk motif tenun, bahasa lokal, dan
ritus adat, Gereja sedang melakukan tindakan pastoral yang sah secara teologis,
menghadirkan misteri keselamatan dengan bentuk-bentuk yang dapat dirasakan,
disentuh, dan dihayati oleh hati umat.
Maka, dalam religiusitas Atoni Pah
Meto, inkulturasi bukanlah sekadar strategi budaya, tetapi perjumpaan kasih
antara Injil dan tanah, antara sabda ilahi dan kebijaksanaan leluhur. Melalui
Bunda Maria, iman itu menemukan bentuknya yang lembut namun kokoh, iman yang
berakar di tanah kering, tetapi berbunga di bawah sinar rahmat Tuhan.
5. Teologi Sosial dan Martabat Petani
Lahan Kering
Mayoritas
Atoni Pah Meto di wilayah Timor Tengah Utara hidup dari tanah kering yang
menuntut ketekunan, kesabaran, dan solidaritas sosial yang tinggi. Tanah bagi
mereka bukan sekadar sumber nafkah, melainkan ruang perjumpaan antara manusia,
alam, dan Tuhan. Dalam konteks ini, teologi sosial Gereja terutama dalam
Ensiklik Mater et Magistra art. 18-20 memberikan dasar reflektif bahwa kerja
manusia di atas tanah merupakan partisipasi dalam karya penciptaan Allah. Enkiklik
tersebut menegaskan martabat manusia sebagai pekerja yang mengambil bagian
dalam rencana ilahi, bukan sekadar penghasil barang ekonomi, melainkan pelaku
cinta kasih sosial yang konkret.
Paus
Yohanes XXIII dalam Mater et Magistra menulis bahwa kerja manusia adalah
“tanda partisipasi dalam penciptaan ilahi dan perwujudan kasih kepada sesama” (signum
participationis in opere divino). Maka, kerja petani lahan kering di Timor
dapat dibaca secara teologis sebagai actus caritatis, tindakan kasih
yang menyatukan manusia dengan ciptaan dan dengan Allah. Di sini, lahan kering
bukan simbol kemiskinan, melainkan locus theologicus, tempat iman diuji
dan diwujudkan dalam ketekunan harian.
Dalam
terang ensiklik Laudato Si’ No.67, relasi petani Atoni Pah Meto dengan
tanah mencerminkan spiritualitas ekologis yang mendalam. Paus Fransiskus
menulis, “tanah adalah karunia yang kita terima dari Tuhan, dan setiap bentuk
kerja di atasnya adalah tindakan pemeliharaan bersama.” Dalam konteks Timor,
para petani membaca tanda-tanda waktu melalui musim kering dan hujan, melalui
kesuburan dan kegersangan, sebagaimana mereka membaca kasih Allah yang
tersembunyi di balik kesulitan hidup. Teologi sosial yang berpihak kepada
petani lahan kering mengundang Gereja untuk tidak hanya berkotbah tentang belas
kasih, tetapi juga meneguhkan keadilan ekologis dan keberlanjutan hidup.
Simbol
kain tenun yang dikenakan pada patung Bunda Maria selama perjalanan keliling di
berbagai lingkungan dalam wilayah Paroki Naesleu menjadi wujud nyata teologi
inkarnasional dari kerja dan martabat. Tenun bukan hanya produk estetika,
tetapi hasil dari perjuangan perempuan di tanah yang keras. Melilitkan kain
tenun pada arca Bunda Maria berarti menghadirkan seluruh jerih payah, doa, dan
solidaritas perempuan Timor di hadapan Allah. Kain itu berbicara tentang tangan
yang bekerja, tanah yang kering, dan iman yang bertahan. Seperti ditulis dalam
studi Obe dan Firmanto, (2020), “kerja tangan petani adalah bentuk doa yang
berkelanjutan, doa yang ditenun dalam panas dan debu.”
Dengan
demikian, martabat petani bukan sekadar soal sosial-ekonomi, melainkan juga soal
teologis dan spiritual. Petani Atoni Pah Meto, dalam menanam di tanah kering,
meneladani Bunda Maria yang dengan rendah hati menerima Sabda dan
menumbuhkannya dalam kehidupan. Maria, yang berziarah ke setiap lingkungan,
tidak hadir sebagai ratu yang jauh, melainkan sebagai ibu (Aina atau Ena)
yang memahami jerih payah di ladang kering dan kebun berbatu. Dalam setiap
sapaan doa rosario di bawah langit Timor yang kering, umat mengakui bahwa kerja
di tanah ini adalah bagian dari mysterium caritatis, misteri kasih yang
menghubungkan langit dan bumi.
Inkulturasi
devosi mariani dengan simbol-simbol agraris dan tekstil lokal memperlihatkan
bahwa iman Katolik di Timor tidak berjarak dari kehidupan riil umat.
Sebaliknya, iman itu bertumbuh di antara tanaman jagung yang menguning, di
tangan para perempuan penenun, dan di hati para petani yang menatap langit
menanti hujan. Teologi sosial yang lahir dari konteks lahan kering seperti ini
menjadi teologi yang membumi, meneguhkan manusia dalam martabatnya dan
menyingkap wajah Allah yang hadir dalam kerja, peluh, dan ketekunan.
6. Kearifan Lokal: Legenda, Konflik,
dan Kasih
Kebudayaan
Atoni Pah Meto kaya akan kisah, simbol, dan ritual yang mengandung kearifan
sosial dan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat, legenda-legenda seperti kisah
Oepunu tidak sekadar cerita masa lampau, tetapi sarana refleksi moral dan
sosial tentang asal-usul relasi manusia, tanah, dan Tuhan. Legenda ini misalnya
menggambarkan hubungan yang rapuh namun selalu diupayakan antara dua komunitas
yang pernah berseteru namun akhirnya bersatu dalam perdamaian melalui ritual
adat. Dalam kerangka ini, kearifan lokal menjadi wahana pendidikan moral dan
pembentukan identitas kolektif Atoni Pah Meto, sebuah “kitab hidup” yang
mengajarkan rekonsiliasi dan kesetiaan terhadap relasi sosial dan kosmik.
Penelitian
etnografi yang dilakukan oleh Liubana dan Nenohai (2020) menegaskan bahwa ritual
adat Atoni berfungsi sebagai “komunikasi sosial” dan “teologi kebersamaan,” di
mana konflik tidak diatasi melalui kekerasan, melainkan melalui ritus penyatuan
(ritual of reconciliation) yang menegaskan kembali relasi kekerabatan.
Dalam ritual itu, simbol-simbol seperti bese (pisau) dan sono
(sendok) menjadi tanda kesepakatan baru, dari alat pemisah menjadi alat
penyatu. Prinsip ini memperlihatkan bahwa kasih dalam konteks Atoni adalah
kasih yang berelasi dan membangun kembali keutuhan. Maka, setiap peristiwa
perdamaian bukan hanya tindakan sosial, melainkan juga tindakan teologis, kasih
yang menebus luka komunitas.
Dalam
masyarakat Timor, tenun juga mengandung nilai perdamaian dan pengakuan sosial.
Motif tenun yang diberikan sebagai tanda perdamaian antar-kampung atau
antar-keluarga mengandung makna bahwa kain menjadi “tubuh sosial” yang
menyelimuti luka, mengikat kembali persaudaraan, dan menyatakan kasih dalam
bentuk yang nyata. Binsasi (2018) menyebutnya sebagai ritual textile of
reconciliation, di mana karya tangan perempuan menjadi sarana komunikasi
lintas waktu dan lintas konflik. Maka ketika kain adat melilit patung Bunda
Maria, ia tidak hanya memperindah rupa Bunda, tetapi juga menyuarakan narasi
rekonsiliasi: Maria hadir sebagai Ibu Perdamaian (Mater Pacis) yang
menenun kembali relasi manusia dengan Allah dan sesama.
Dalam
terang Kitab Suci, makna rekonsiliasi ini berakar dalam ajaran kasih yang
menyembuhkan perpecahan. Rasul Paulus menulis: “Sebab Allah mendamaikan kita
dengan diri-Nya oleh Kristus dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu
kepada kami” (2Kor 5:18). Spirit ini hidup dalam budaya Atoni, di mana
rekonsiliasi bukan sekadar tindakan hukum, tetapi ritus suci yang menandai
pemulihan relasi yang rusak. Dalam konteks pastoral, penghormatan kepada Bunda
Maria dengan kain adat menjadi simbol Gereja yang mengakui kearifan lokal
sebagai bagian sah dari pewartaan kasih Kristus, Evangelium inculturatum
yang berakar di tanah Timor.
Konsili
Vatikan II dalam Gaudium et Spes menegaskan bahwa Gereja “menghargai
segala hal yang benar, baik, dan indah dalam kebudayaan lokal, karena semuanya
berasal dari Roh Kudus yang bekerja dalam sejarah umat manusia” (GS, n. 44).
Maka, pengakuan terhadap legenda, simbol, dan ritus perdamaian dalam budaya
Atoni bukan bentuk kompromi teologis, melainkan penghargaan terhadap Roh yang
bekerja dalam sejarah bangsa Timor. Gereja yang memeluk kain adat di tubuh
Bunda Maria sesungguhnya sedang memeluk sejarah umat, luka kolektif, dan
kerinduan untuk damai.
Dengan
demikian, teologi kasih di tanah Timor berjumpa dengan kearifan lokal Atoni Pah
Meto dalam satu gerak yang sama, menenun kembali relasi yang rusak, memulihkan
luka sosial, dan menghidupkan kembali rasa persaudaraan. Dalam legenda,
konflik, dan ritual adat, kasih bukan konsep abstrak, melainkan pengalaman
konkret yang dihayati dan diwartakan melalui tubuh budaya. Bunda Maria, yang mengunjungi
setiap lingkungan dengan balutan tenun khas Atoni, menjadi ikon kasih yang
menyejukkan tanah kering, kasih yang menghidupkan, menyatukan, dan meneguhkan
umat di tengah keterbatasan.
7. Keindahan Menyelamatkan: Pesan
Teologis
Dalam
tradisi iman Katolik, keindahan bukanlah sekadar perkara estetika, melainkan
wujud nyata dari kebenaran dan kebaikan ilahi. Keindahan rohani Maria sebagai Bife
Amasat, perempuan yang elok hati, memancarkan apa yang oleh para teolog
disebut sebagai pulchritudo salvifica, yakni keindahan yang
menyelamatkan. Dalam diri Maria, umat melihat bukan hanya wajah seorang ibu,
tetapi cahaya kasih Allah yang menembus kekeringan hidup dan menumbuhkan
harapan di tanah yang gersang. Julukan Bife Amasat Pah Meto yang lahir
dari rahim budaya Atoni Pah Meto khususnya yang dilaksanakan oleh umat Paroki
Naesleu, dengan demikian menjadi simbol iman yang kontekstual, Allah hadir
dalam keindahan yang sederhana, dalam kelembutan seorang ibu, dan dalam
kekuatan iman yang bertahan di tengah tanah kering.
Paus
Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Mater menulis bahwa Maria adalah
ikon Gereja dalam ziarah iman, cermin jiwa yang terbuka kepada rahmat dan
kebenaran. Keindahannya bukan berasal dari dunia, melainkan dari kesetiaan pada
Sabda yang menjelma. Dalam konteks teologi inkarnasi, Maria adalah ruang di
mana Verbum caro factum est, Sabda menjadi daging, dan keindahan Ilahi
menjelma dalam tubuh manusia. Maka, Bife Amasat bukan hanya gelar
kultural, tetapi penegasan teologis tentang bagaimana Allah memilih untuk
menampakkan diri melalui yang indah, lembut, dan manusiawi. Bife Amasat adalah
keindahan yang mengundang, bukan yang memaksa; keindahan yang membebaskan,
bukan yang menindas.
Bagi
umat Naeleu, keindahan Maria bukanlah kemewahan visual, melainkan kesetiaan
eksistensial. Dalam kerasnya kehidupan di tanah kering (Pah Meto),
keindahan berarti keteguhan untuk tetap percaya, bekerja, dan mencintai. Maria
menjadi tanda bahwa iman yang indah adalah iman yang bertahan dalam penderitaan,
sebagaimana cendana wangi yang hidup di tanah tandus. Dengan menenun kain dan
melilitkannya pada arca Maria, umat menyatakan bahwa kasih dan kerja keras
adalah persembahan keindahan bagi Tuhan, sebuah bentuk ars divina, seni
kehidupan yang menguduskan yang biasa menjadi yang ilahi.
Dari
perspektif teologi kontemporer, Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ No. 97
menekankan bahwa keindahan ciptaan adalah jalan menuju perjumpaan dengan Allah:
“Ketika kita berhenti mengagumi keindahan ciptaan, kita kehilangan kemampuan
untuk bersyukur kepada Sang Pencipta.” Maka, Bife Amasat Pah Meto bukan
hanya pujian bagi Maria, tetapi pernyataan iman ekoteologis, bahwa di tengah
kekeringan bumi, Allah masih menyalakan api kasih yang indah dan menyelamatkan.
Maria, sang ibu, menjadi saksi bahwa keindahan sejati tidak musnah dalam
keterbatasan, melainkan justru lahir darinya.
Dalam
semangat inkulturasi, Gereja di Naesleu dan seluruh Timor Tengah Utara sedang
menulis ulang kisah keindahan Maria dalam bahasa budaya sendiri. Keindahan yang
mereka rayakan tidak asing atau dipaksakan, tetapi lahir dari pengalaman
konkret tentang kasih, kerja, dan harapan. Dalam teologi Atoni Pah Meto,
keindahan selalu terhubung dengan relasi, dengan tanah, leluhur, dan Tuhan.
Maka, Bife Amasat Pah Meto dapat dibaca sebagai bentuk lokal dari pulchritudo
Ecclesiae, keindahan Gereja yang hidup dalam tubuh budaya.
Dengan
demikian, keindahan Maria menyelamatkan karena mempertemukan yang ilahi dan
yang manusiawi, yang universal dan yang lokal, yang kudus dan yang duniawi. Maria
mengundang manusia untuk melihat kembali bahwa kasih Allah selalu hadir dalam
keindahan hidup sehari-hari, dalam kerja tangan petani, dalam tenunan
perempuan, dalam kesetiaan ibu, dan dalam doa umat di tanah kering. Keindahan
ini bukan pelarian dari realitas, tetapi kekuatan untuk mentransformasikannya,
sebagaimana Maria, yang dalam keindahan imannya, melahirkan keselamatan bagi
dunia.
........................
Malam
perlahan menua di Naesleu. Angin dari perbukitan Timor membawa aroma tanah
kering yang bersatu dengan wangi dupa cendana dan serat kain tenun yang
membalut lembut bahu arca Maria. Cahaya lilin menari di wajah Bife Amasat
Pah Meto, menciptakan bayangan yang hidup di antara wajah-wajah umat yang
bersujud dalam diam. Dalam keheningan itu, doa-doa naik bukan hanya sebagai
kata, melainkan sebagai anyaman kasih antara bumi dan surga.
Maria
berdiri dan hadir di tengah umatnya bukan sebagai sosok jauh di langit, tetapi
sebagai Bife Pah Pinan, ibu tanah dan ibu bumi, yang mengerti getirnya
musim kemarau, beratnya ladang berbatu, dan hangatnya solidaritas di antara
mereka yang setia berharap. Di balik setiap helai kain tenun yang
menyelimutinya, tersimpan kisah perempuan-perempuan Atoni yang menenun hidup
dengan kesabaran dan cinta, sebagaimana Maria menenun sejarah keselamatan
dengan fiat sucinya “Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu” (Luk 1:38).
Bife
Amasat Pah Meto menjadi simbol iman yang tidak lahir
dari kemewahan, melainkan dari keteguhan, iman yang tumbuh dari tanah keras dan
tetap berbuah kasih. Di dalam gelar itu, keindahan dan kesetiaan bersatu,
keindahan yang lahir dari penderitaan, dan kesetiaan yang menemukan bentuknya
dalam cinta yang melayani. Seperti ditulis Paus Fransiskus dalam Laudato Si’
No. 241, Maria “menjaga dunia yang rapuh dan memeluknya dengan kasih seorang
ibu.” Maria hadir di setiap lingkungan dalam wilayah Paroki Naesleu bukan hanya
untuk dilihat, tetapi untuk mengajarkan cara mencintai dengan sabar, dengan
lembut, dan dengan harapan yang tidak padam.
Ketika
patung itu berpindah ke lingkungan lain, yang tertinggal bukan hanya jejak
langkahnya, tetapi jejak iman yang hidup. Doa Rosario yang bergema di setiap
malam, yang terlontar dari mulut umat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dari
berbagai lingkungan menjadi nyanyian kesetiaan yang melampaui waktu. Dalam
setiap butir doa dan setiap simpul tenun, umat menyadari bahwa kasih Allah
benar-benar telah menjelma dalam budayanya bahwa Maria, Bife Amasat Pah Meto,
adalah wajah keindahan Allah yang menyapa tanah kering dengan kelembutan air
kehidupan.
Maka
dari Naesleu, dari tanah yang keras namun penuh rahmat, bergema pesan abadi
bagi seluruh Gereja, bahwa kasih yang ditenun dalam iman dan budaya mampu
menyelamatkan dunia. (KU)
Tag
Berita Terkait

LEBENSWELT TABUA: KOSMOLOGI KEBERSAMAAN ATONI PAH METO DALAM CERMIN FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

Tag
Arsip
Kue Pelangi Menakjubkan Terbaik
Final Piala Dunia 2022
Berita Populer & Terbaru
Jajak Pendapat Online