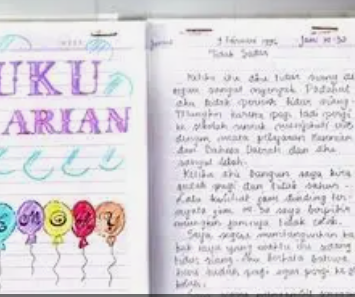TANAH:
ALTAR KERJA
Dalam beberapa tahun terakhir, tanah Indonesia menjadi saksi dari berbagai bencana: banjir bandang, longsor dan hujan ekstrem yang merenggut nyawa serta menghancurkan kehidupan. Di Sibolga, tanah yang dahulu menopang penghidupan berubah menjadi arus lumpur yang menelan apa pun di hadapannya. Peristiwa semacam ini bukan sekadar gejala alam melainkan cermin dari krisis kesadaran manusia modern terhadap bumi. Tanah yang dahulu dihormati sebagai “ibu kehidupan,” kini diperlakukan sebagai alat produksi yang dieksploitasi tanpa nurani. Ketika relasi spiritual dengan bumi terputus, kesakralan tanah pun memudar. Bencana menjadi cara alam berbicara, memanggil untuk kembali mengingat siapa yang sesungguhnya terluka.
Sebagaimana ditegaskan dalam Laudato Si’
(Franciscus, 2015, art. 2), “ketika kita menyakiti bumi, kita juga menyakiti
diri kita sendiri.” Dalam terang Kejadian 2:15, manusia ditugaskan untuk
“mengusahakan dan memelihara taman itu,” bukan menguasainya. Krisis ekologis
sesungguhnya adalah krisis spiritual yang berakar pada kelalaian terhadap
panggilan ini.
Dalam pandangan kosmologis Nusantara, tanah
tidak pernah sekadar unsur fisik, melainkan ruang sakral tempat kehidupan
ditenun. Teologi kontekstual bergaung di dalam pandangan ini, bahwa iman sejati
harus berakar pada bumi tempat langkah berpijak. Tanah adalah altar, dan kerja
adalah persembahan. Mengolah tanah dengan hormat berarti merayakan liturgi
kehidupan, tempat yang lahiriah dan batiniah menyatu.
Spiritualitas ekologis menegaskan bahwa
bekerja di tanah adalah tindakan iman, panggilan untuk menjaga bukan
menaklukkan, serta merawat bumi sebagai perpanjangan kasih Sang Pencipta
(Deane-Drummond, 2016). Seperti diungkapkan dalam Mazmur 24:1, “Tuhanlah yang
empunya bumi serta segala isinya.” Maka bekerja di tanah adalah partisipasi
dalam liturgi ciptaan, di mana manusia menjadi imam bagi bumi (Gaudium et
Spes, art. 34).
Tanah adalah rahim kosmik yang melahirkan
dan memelihara kehidupan. Busro (2025) menyebut kerja ekologis sebagai dzikir
tubuh, pujian yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Kwok Pui-lan
(2019) menggambarkan bumi sebagai tubuh feminin yang memberi dan melindungi
kehidupan. Pandangan ini beresonansi dengan kosmologi Atoni Pah Meto
yang memahami pah (tanah) sebagai bagian dari tubuh kehidupan yang
dijaga oleh Uis Neno (Tuhan Langit) dan Uis Pah (Tuhan Tanah).
Tanah ulayat bukan milik pribadi tetapi
warisan sakral yang menghubungkan leluhur, manusia kini dan generasi mendatang
(Wula et al., 2022). Dalam terang Kitab Suci, manusia diciptakan “dari debu
tanah” (Kejadian 2:7), dan kepada tanah pula ia akan kembali. Kesadaran ini
membentuk kerendahan hati ontologis bahwa kita bukan pemilik melainkan bagian
dari ciptaan yang lebih besar.
Dalam kehidupan masyarakat Atoni Pah Meto, bekerja di tanah bukan sekadar mencari hasil, tetapi menyentuh misteri semesta. Empat belas ritus pertanian di Maubesi, mulai dari memilih lahan, meminta izin, menebas, hingga menanam, menunjukkan bahwa setiap gerak tubuh memiliki makna doa (Taum, 2004). Mencangkul berarti memohon kehidupan, menanam berarti menaruh harapan dan memanen berarti mengucap syukur.
Kerja menjadi pengakuan iman yang dihidupi melalui tindakan, di mana tubuh manusia menjadi jembatan antara bumi dan langit (Viktoria, Nono, & Olla, 2024). Gaudium et Spes (art. 67) menegaskan bahwa melalui kerja manusia “berpartisipasi dalam karya penciptaan.” Maka kerja, dalam terang iman dan adat, bukan beban ekonomis tetapi liturgi ekologis.
Kerja yang sejati memberi kehidupan, bukan mengurasnya. Petani Atoni Pah Meto mengenali karakter tanah melalui warna dan sifatnya: tanah merah menghidupi, tanah putih menenangkan dan tanah hitam menghangatkan (Korbaffo & Sengkoen, 2023). Prinsip ini memuat kebijaksanaan ekologis yang tidak memisahkan manfaat dari moralitas.
Sebaliknya, kerja yang digerakkan oleh kerakusan menjadikan tanah sekadar objek
yang dihisap tanpa empati. Laudato Si’ (art. 82) mengingatkan bahwa
“sikap konsumeristik membuat bumi tampak seperti barang yang bisa dibuang.”
Ketika kerja kehilangan etika, bumi kehilangan martabatnya. Spiritualitas
ekologis menumbuhkan kesadaran bahwa merawat tanah berarti merawat kemanusiaan (Amsal
12:11).
Ritus-ritus dalam tradisi Atoni Pah Meto,
seperti tof lele, doa bersama tobe sebagai penjaga tanah atau
permohonan izin sebelum membuka lahan adalah bahasa relasional antara manusia,
alam dan Yang Ilahi. Setiap upacara menjadi pengingat bahwa kerja memerlukan
kerendahan hati dan penghormatan terhadap kehidupan.
Dalam tradisi itu, tanah menjadi altar
tempat kerja, syukur dan harapan dipersembahkan. Melalui adat, manusia belajar
menempatkan diri bukan sebagai penguasa atas tanah, tetapi sebagai bagian dari
jaringan kehidupan (Nordholt, 1971; Wula et al., 2022). Tradisi ini sejalan
dengan visi Compendium of the Social Doctrine of the Church (art. 463),
yang menegaskan bahwa kebudayaan lokal adalah “tempat di mana iman menjelma
dalam solidaritas terhadap ciptaan.”
Teologi ekologis menempatkan tanah sebagai
anugerah yang harus dijaga dengan rasa hormat. Deane-Drummond (2016) menegaskan
bahwa bumi adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dipelihara, bukan
dikuasai secara mutlak. Siregar (2024) menambahkan bahwa kerusakan ekologis
adalah bentuk dosa struktural yang melukai relasi antara ciptaan dan Pencipta.
Dalam pandangan Atoni Pah Meto,
penguasa tanah sejati adalah Uis Pah, sementara manusia hanyalah
penatalayan yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi (Viktoria et al.,
2024). Mazmur 8:6 mengingatkan, “Engkau membuat dia berkuasa atas buatan
tangan-Mu,” tetapi kekuasaan itu harus dijalankan dalam kasih dan tanggung
jawab.
Seluruh refleksi ini berpuncak pada kesadaran bahwa tanah adalah altar tempat kerja manusia berubah menjadi doa. Mengolah bumi dengan kasih dan tanggung jawab berarti ikut serta dalam karya penciptaan. Kerja menjadi tindakan sakramental yang menyatukan ekologi, ekonomi, dan teologi dalam satu kesadaran kosmik. Laudato Si’ (art. 236) menegaskan bahwa Ekaristi “menghubungkan langit dan bumi, merangkul dan menembus seluruh ciptaan.” Maka setiap kerja di tanah, bila dilakukan dengan kasih, menjadi bentuk “ekaristi ekologis” doa yang diwujudkan dalam tindakan.
Dari kesadaran ini lahir seruan spiritual, kembalikan tanah kepada martabat sucinya dan kembalikan kerja kepada maknanya sebagai ibadah. Tanah tidak boleh diperlakukan sebagai objek industri melainkan sebagai tubuh kehidupan yang memiliki ingatan dan martabat. Merawat tanah berarti meneguhkan iman dan moralitas sebab tanah adalah penghubung antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Dalam tindakan sederhana menjaga bumi, kehidupan bersama dipulihkan (Taum, 2004; Wula et al., 2022). Inilah wujud nyata dari “pertobatan ekologis” yang diundang oleh Paus Fransiskus, pertobatan yang mengubah hati, bukan hanya kebiasaan.
Tanah mengajarkan bahwa bekerja adalah bentuk doa dan menyentuh bumi berarti menyentuh wajah Tuhan. Dalam dunia yang rapuh oleh bencana ekologis, pemulihan spiritual hanya mungkin lahir dari relasi baru dengan tanah. Tanah adalah altar, kerja adalah liturgi, dan kehidupan adalah ibadah. Di sanalah harmoni antara iman, adat dan bumi menemukan bentuknya, menuntun manusia untuk hidup selaras dengan irama ciptaan (Roma 8:19–21). Seperti dinyatakan dalam Laudato Si’ (art. 244), “Di akhir hidup, kita akan bertemu dengan setiap makhluk yang hidup dan bersama mereka memuji Tuhan.”
*Batas Kota, pagi di awal Desember 2025, KU
Tag
Berita Terkait

LEBENSWELT TABUA: KOSMOLOGI KEBERSAMAAN ATONI PAH METO DALAM CERMIN FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ

Tag
Arsip
Kue Pelangi Menakjubkan Terbaik
Final Piala Dunia 2022
Berita Populer & Terbaru
Jajak Pendapat Online